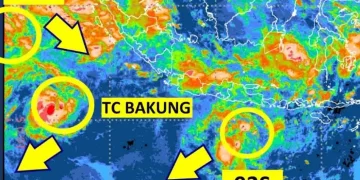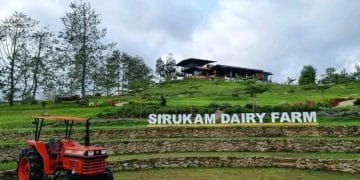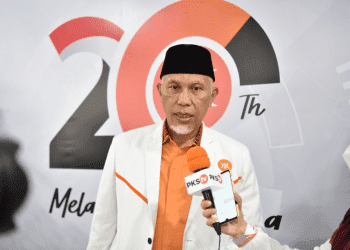Oleh : Ar Rafi Saputra Irwan
Suku Anak Dalam (sering juga disebut Orang Rimba, Orang Kubu di beberapa literatur) adalah kelompok masyarakat adat yang tersebar di beberapa provinsi Sumatera (termasuk Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan populasi di Sumatera Barat). Mereka dikenal karena keterkaitan hidupnya yang kuat dengan hutan, pola mata pencaharian berbasis sumber daya alam, serta posisi sosial-ekonomi yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan kebijakan pembangunan.
Beberapa studi etno-historis dan tesis lokal menunjukkan adanya narasi beragam tentang asal-usul SAD: ada versi yang mengaitkan leluhur SAD dengan kelompok-kelompok yang bermigrasi dari dataran Pagaruyung (Sumatera Barat) ke hutan-hutan pedalaman dan ada pula penafsiran yang menempatkan mereka sebagai kelompok pemburu-pengumpul lokal yang berinteraksi lama dengan masyarakat agraris di sekitarnya. Persoalan asal-usul ini masih menjadi bahan penelitian antropologis dan sejarah lokal.
SAD umumnya tersusun dalam unit-unit keluarga kecil yang bersifat kinship-based; kepemimpinan tradisional (tumenggung, pengurus adat setempat dalam beberapa area) tetap ada pada komunitas yang sudah lebih menetap, sementara kelompok lain masih mempertahankan mobilitas tinggi. Bahasa dan kosakata SAD menunjukkan pengaruh dan variasi regional penutur tersebar di beberapa provinsi sehingga ada perbedaan dialek dan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan hidup mereka.
Secara tradisional, kehidupan ekonomi SAD bergantung pada hutan: berburu, mengumpulkan hasil hutan (buah, rotan, obat), berkebun ladang berpindah, dan kadang bertani skala kecil. Namun, alih fungsi hutan (perambahan, konversi menjadi perkebunan sawit, infrastruktur jalan) telah mengurangi akses mereka ke sumber-sumber ini. Akibatnya banyak kelompok SAD menghadapi kelangkaan pangan, tekanan terhadap mata pencaharian, serta kecenderungan menumpang di kebun milik penduduk atau perusahaan.
Penelitian lapangan dan studi kesehatan menunjukkan bahwa akses SAD terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih terbatas masalah geografis (lokasi terisolasi), budaya, dan administratif (banyak anggota belum tercatat/belum memiliki dokumen kependudukan lengkap) memperburuk kondisi. Intervensi layanan kesehatan yang sensitif budaya dan program pendidikan inklusif telah dijalankan oleh beberapa puskesmas dan LSM, namun cakupannya belum merata.
Awalnya banyak kelompok SAD mempraktikkan kepercayaan animisme/dinamisme lokal. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi perubahan termasuk proses islamisasi atau adopsi agama-agama resmi yang dipengaruhi oleh dakwah, interaksi dengan masyarakat mayoritas, dan kebijakan negara. Pergeseran keyakinan ini sering ikut merubah praktik-praktik adat, sistem ritual, dan struktur sosial komunitas.
Literatur sosial menunjukkan pola marginalisasi historis: konflik akses lahan dengan desa-desa tetangga, perusahaan perkebunan, dan kebijakan negara kerap menempatkan SAD pada posisi rentan. Konflik ini muncul karena klaim penggunaan lahan yang berbeda (adat vs. hukum formal), serta karena SAD sering tidak memiliki sertifikat tanah atau dokumen hukum yang diakui negara. Studi kasus di beberapa koridor lintas Sumatera menggambarkan bagaimana fragmentasi kelompok dan tekanan ekonomi memperparah kerentanan mereka.
Beragam program pemerintah daerah, LSM, dan organisasi bantuan mencoba memperbaiki kondisi SAD: mulai dari pendaftaran administrasi kependudukan, program pendidikan berbasis kearifan lokal, layanan kesehatan mobile, hingga inisiatif pengakuan hak-hak adat. Keberhasilan program cenderung lebih baik ketika intervensi dirancang partisipatif mendengar aspirasi masyarakat, menghormati praktik adat, dan menyesuaikan model layanan dengan mobilitas komunitas. Dokumentasi budaya dan kajian etnografi (oleh balai-balai budaya dan akademisi lokal) juga berperan dalam menjaga pengetahuan tradisional.
Suku Anak Dalam di Sumatera Barat adalah bagian dari mosaik etnis di Sumatera yang kehidupan tradisionalnya terkait erat dengan hutan dan sumber daya alam. Mereka menghadapi tekanan serius dari perubahan lingkungan, pembatasan akses layanan publik, dan marjinalisasi sosial-ekonomi. Penanganan yang efektif harus menghormati hak adat, melibatkan komunitas secara partisipatif, dan menyelaraskan program pembangunan dengan pelestarian budaya.
Referensi
Balai Pelestarian Nilai Budaya — kajian Suku Anak Dalam di Kabupaten Dharmasraya
MT Sari (studi persepsi layanan kesehatan pada Suku Anak Dalam). Neliti.
Neliti
Tresno, T. (tesis/penelitian etno-forestri, Univ. Andalas) — studi tentang orang rimba / keterkaitan ekologis.
ResearchGate — kajian konflik sosial dan marginalisasi Suku Anak Dalam (berbagai artikel dan prosiding).
Laporan kemitraan/NGO tentang inklusi Suku Anak Dalam di koridor Trans-Sumatera.