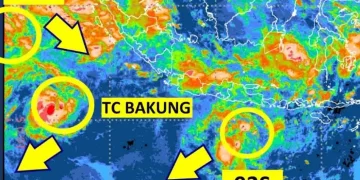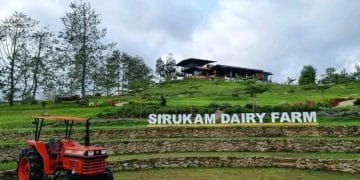Klaim bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun telah tertanam kuat dalam ingatan kolektif bangsa. Namun menurut penelitian ahli seperti G. J. Resink, narasi itu perlu diluruskan karena tidak sesuai fakta historis.
Penelitian Resink—ahli hukum internasional keturunan Belanda-Indonesia—menunjukkan bahwa angka “350 tahun” berasal dari generalisasi yang kurang berdasar.
Ia mencatat bahwa kedatangan orang Belanda di Nusantara bukan langsung diterjemahkan sebagai penjajahan. Sebagai contoh, pada 1596 Cornelis de Houtman tiba di Banten bukan dalam rangka menjajah, melainkan berdagang.
Lebih lanjut, sejumlah wilayah di Nusantara masih merdeka secara hukum dan politik hingga akhir abad XIX dan awal abad XX. Misalnya, wilayah seperti Aceh baru ditaklukkan Belanda sekitar 1903–1904.
Sejarawan lain seperti Dr. Lilie Suratminto dan Dr. Sri Margana menambahkan bahwa masa “kolonial Belanda murni” jika dihitung dari saat pemerintah Hindia Belanda berdiri secara resmi lebih pendek, yakni sekitar 126–142 tahun.
Dari perspektif Sumatera Barat khususnya, narasi “350 tahun penjajahan” juga berimplikasi pada bagaimana generasi muda menginterpretasi perjuangan dan kemerdekaan. Jika masa penjajahan secara faktual jauh lebih pendek, maka wacana tentang akar-ketertindasan, pembelajaran sejarah lokal, dan kesadaran kolektif perlu diperbarui.
Kritik reflektif
Narasi 350 tahun menjajah tidak hanya mengenai angka; ia juga berkaitan dengan bagaimana bangsa membingkai kisah penaklukan, perlawanan, dan kemerdekaan. Versi sejarah yang terlalu sederhana tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi di tiap wilayah berpotensi menutup ruang berpikir kritis.
Pemahaman bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun perlu direvisi berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Memperbarui narasi sejarah bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kejujuran terhadap kompleksitas masa lalu dan bagaimana kita membangun identitas masa depan di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia.